Senyum Terakhir di Pasupati
Oleh:
Ummu Fahhala
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
Terasjabar.co – Langit Bandung sore itu muram. Angin berhembus pelan, menelusup di antara deru kendaraan yang melintas di atas Flyover Pasupati. Di bawah langit jingga yang kian redup, seorang remaja berdiri diam di tepi jembatan itu sendiri, dengan tatapan kosong ke arah horizon kota.
Pemuda berusia 19 tahun, sebutlah Karel, dia dikenal ramah di lingkungannya, tapi belakangan sering tampak murung. Tak banyak yang tahu, bahwa di balik senyum tipisnya tersimpan perang batin yang tak terlihat.
Dialog Sunyi di Tepi Dunia
“Karel, kamu nggak apa-apa?” tanya Dimas, sahabatnya, seminggu sebelum kejadian itu. Mereka duduk di taman kampus, ditemani sisa senja dan suara jangkrik yang mulai menggeliat.
Karel menatap jauh ke arah gedung-gedung tinggi.
“Kadang aku ngerasa… dunia ini bising banget, Mas. Tapi anehnya, di tengah kebisingan itu, aku malah ngerasa sepi.”
“Sepi kenapa, Rel?”
“Karena kayaknya… nggak ada yang benar-benar denger,” jawabnya pelan.
Dimas tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu temannya sedang terluka, tapi tak tahu harus menolong dari mana. Seperti jutaan orang lain di dunia modern, mereka terhubung lewat layar, tapi terputus di hati.
Seminggu kemudian, pagi Bandung dikejutkan kabar duka. Seorang remaja ditemukan tewas gantung diri di Flyover Pasupati.
Di media sosial, berita itu menjadi viral. Banyak yang berkomentar: “Kasihan banget.” “Pasti karena tekanan hidup.” “Kenapa nggak curhat aja?”
Namun di balik simpati yang meluap, tak banyak yang sungguh-sungguh merenung: apa yang salah dengan dunia kita hari ini?
Polsek Bandung Wetan, mengonfirmasi identitas korban dan menyebut penyelidikan masih dilakukan untuk mencari motif pasti.
Namun motif sejati mungkin tak akan pernah ditemukan dalam berkas penyidikan. Karena yang mati bukan hanya tubuh, tapi harapan secara perlahan, di tengah kehidupan yang semakin kehilangan makna.
Masalah ini bukan sekadar tentang depresi pribadi. Ia adalah simptom dari peradaban yang kehilangan arah.
Kita hidup di zaman di mana nilai manusia diukur dari saldo rekening, pencapaian akademik, dan jumlah pengikut di media sosial.
Pendidikan sibuk mencetak “pemenang lomba hidup,” tapi lupa mengajarkan arti hidup.
Sistem ekonomi memuja pertumbuhan, tapi menelantarkan kesejahteraan batin.
Negara bekerja keras menciptakan lapangan kerja, tapi banyak rakyat yang justru kehilangan makna bekerja itu sendiri.
Di tengah hiruk pikuk pembangunan, jiwa manusia seakan tak punya tempat.
Dan ketika batin mulai kosong, setan berbisik pelan: “Sudahlah, akhiri saja…”
“Kenapa harus hidup, kalau tiap hari cuma berjuang buat bertahan?” tulis Karel di catatan terakhirnya singkat, tapi menampar nurani siapa pun yang membacanya.
Bukan hanya Karel yang merasa seperti itu.
Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan peningkatan kasus bunuh diri di Indonesia setiap tahun.
Aktivis muda Nadira Aisyah, S.Pd., menyebut bahwa depresi telah menjadi masalah sosial struktural, bukan sekadar persoalan pribadi. “Kita hidup dalam sistem yang membuat manusia berkompetisi, bukan berempati,” ujarnya. “Dan selama akar itu tidak dicabut, luka-luka seperti ini akan terus berdarah.”
Cahaya Harapan di Tengah Gelap
Namun Islam mengajarkan, tak ada malam yang abadi. Allah Swt. berfirman: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa [4]: 29)
Ayat ini bukan sekadar larangan, tapi seruan kasih. Bahwa hidup, betapapun pahit, selalu punya alasan untuk dilanjutkan, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya.
Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah seorang hamba tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya”, (HR Bukhari dan Muslim)
Islam menolak pandangan bahwa hidup hanya tentang bertahan. Hidup adalah perjalanan menuju ridha Allah, tempat setiap kesulitan menjadi peluang untuk bertumbuh dalam iman.
Namun, menjaga jiwa bukan hanya tugas individu. Rasulullah Saw. bersabda, “Imam adalah gembala, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya”. (HR Bukhari dan Muslim)
Negara sejatinya hadir untuk menjamin kehidupan yang layak, mencakup pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bahkan perlindungan terhadap kesehatan mental.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah pelindung, bukan penguasa. Ia hadir untuk meringankan beban rakyatnya, bukan menambah luka.
Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan mental dan sosial. Tapi, kerja ini harus dibingkai dengan nilai kemanusiaan dan spiritualitas, bukan sekadar administrasi.
Sebab, rakyat tak hanya butuh makan, tapi juga makna.
Sore itu, di tepi Flyover Pasupati, sehelai surat kecil tertiup angin. Tulisan di atasnya pudar, tapi masih terbaca: “Kalau saja dunia ini sedikit lebih hangat, mungkin aku masih mau tinggal.”
Barangkali, pesan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kita semua, agar belajar mendengar sebelum kehilangan, agar kembali menata hati sebelum terlalu jauh berjalan.
Kita semua sedang hidup dalam dunia yang penuh suara, tapi keselamatan ada pada mereka yang berani mendengarkan nurani.
Dan satu-satunya tempat bagi jiwa yang letih hanyalah kembali kepada Allah, yang Maha Menyembuhkan segala luka.
Karena di saat dunia tak lagi memeluk, hanya Dia yang masih terbuka untuk setiap air mata.





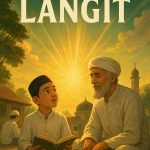
Leave a Reply